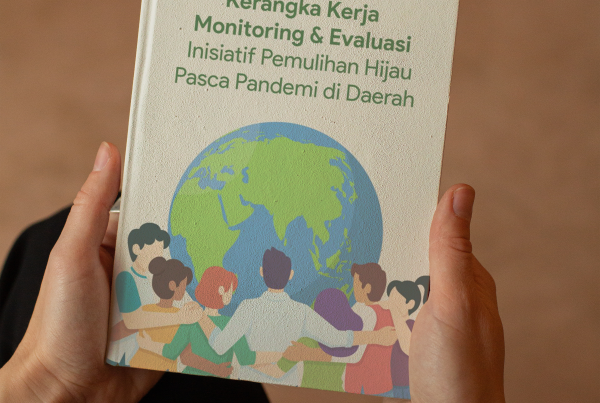Apa yang kita harapkan dari negara dengan jumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, curah hujan ekstrim, badai, puting beliung, kebakaran hutan, dan gelompang pasang air laut (rob) yang sangat tinggi? Kita menyebutnya bencana ekologi karena lebih banyak disebabkan oleh krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang masif dan tak terbendung. Apa yang kita harapkan dari negara dengan jumlah konflik agraria dan tenurial yang semakin hari semakin meluas? Apa yang kita harapkan dari negara yang selalu mengumbar janji manis target perhutanan sosial, pertanian organik berkelanjutan, dan kelestarian hutan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggelayut dalam pikiran dan menjadi keresahan di tengah Indonesia yang mencanangkan sebuah perubahan besar, Indonesia Emas 2045. Menghadapi krisis iklim, ketimpangan sosial, dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam, negeri ini ditantang untuk melakukan transformasi menuju Ekonomi Hijau yang inklusif dan berkeadilan.
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menyatakan arah pembangunan ke depan menuju ekonomi hijau (dan ekonomi biru). Agenda ini tidak hanya menjanjikan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan transisi energi, tetapi juga menyasar penguatan ekonomi kerakyatan—termasuk perhutanan sosial (PS), pertanian berkelanjutan, dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Intinya, Ekonomi Hijau yang digagas bukan sekadar persoalan teknokratik, tetapi merupakan komitmen pemerintah untuk menyelaraskan pembangunan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tentunya komitmen tersebut perlu ditopang juga dengan penegakan hukum yang kuat dan konsisten.
Namun, narasi hijau yang digaungkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab kerumitan di lapangan. Di berbagai wilayah Indonesia, masyarakat adat masih kehilangan tanahnya karena ekspansi “proyek hijau” pemerintah atau korporasi. Hutan masih ditebang atas nama investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dana publik seringkali tidak mengalir ke komunitas-komunitas yang telah terbukti menjaga alam selama ratusan tahun.
Di sinilah pentingnya memastikan bahwa komitmen fiskal negara benar-benar menyentuh akar rumput, bukan sekadar berhenti pada laporan dan indikator makro. Hal ini menjadi sorotan dalam tulisan Eko Cahyono dan Delima Silalahi, Peneliti Senior Sajogyo Institute (SAIN Bogor) dan Direktur Eksekutif KSPPM Sumatera Utara.
Ekonomi Hijau: Dari Wacana ke Aksi Nyata
Konsep Ekonomi Hijau yang inklusif tidak bisa hanya menjadi jargon. Ia harus menjiwai struktur fiskal negara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan berbagai instrumen seperti Climate Budget Tagging (CBT), pendanaan adaptasi-mitigasi melalui BPDLH, dan penerbitan green bond. Bahkan, transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Fiskal (DIF), kini diarahkan untuk mendukung agenda hijau. Komitmen ini turut disampaikan Lisno Setiawan, perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dalam Bunga Rampai ini.
Meski demikian, efektivitas skema-skema tersebut masih terbatas, belum menyentuh akar permasalahan. Persoalan yang umum terjadi adalah kurangnya sinergi antar-K/L, lemahnya pelacakan data (tagging) anggaran iklim, dan minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam desain program, yang membuat sebagian inisiatif tersebut berjarak dari realita. Contohnya, pendanaan hijau untuk sektor pertanian belum mampu mendorong transformasi yang signifikan. Tanaman pangan—yang menjadi sandaran jutaan petani—terus mengalami kontraksi pertumbuhan.
Ironisnya, sebagian besar anggaran justru terserap untuk program yang minim inovasi dan tak berorientasi pada mitigasi iklim. Padahal, sektor ini sangat rentan terhadap perubahan iklim dan membutuhkan pendekatan baru yang menyatukan konservasi, teknologi, dan kesejahteraan petani. Hal ini disampaikan secara lugas oleh Mohammad Faisal dari CORE Indonesia dan Prof. Bustanul Arifin, Guru Besar UNILA sekaligus Ekonom Senior INDEF.
Titik Ukur Keadilan Fiskal
Seiring menguatnya narasi Ekonomi Hijau, masyarakat adat seharusnya tidak hanya menjadi objek. Mereka jelas adalah subjek pembangunan yang sejak lama hidup harmonis dengan alam. Namun, proyek-proyek seperti REDD+, perdagangan karbon, hingga pembangunan eco-tourism justru sering merampas wilayah adat atas nama konservasi atau investasi hijau.
Kita kembali diingatkan oleh Eko Cahyono dan Delima Silalahi tentang Gerakan “No Rights, No REDD” yang menegaskan bahwa tanpa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, segala bentuk skema karbon akan melanggengkan kolonialisme hijau. Komitmen fiskal negara pun perlu menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa wilayah adat adalah ekosistem hidup yang tidak bisa direduksi hanya sebagai penyerap karbon.
Perhutanan Sosial (PS) menjadi salah satu solusi kunci. Skema ini seyogyanya berupaya memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola lahan secara lestari. Tetapi, program ini sering kali terhambat oleh birokrasi, minimnya pendanaan, sampai dengan lemahnya pengawasan.
Komitmen fiskal seharusnya mengalir untuk memperkuat kapasitas komunitas, membangun infrastruktur dasar, dan menciptakan skema insentif yang menghargai praktik-praktik lokal yang terbukti menjaga hutan, seperti yang ditegaskan oleh M. Yasir Sani, Manajer Program Kemitraan.
Salah satu kegagalan utama kebijakan fiskal selama ini adalah pendekatannya yang terlalu bertumpu pada pertumbuhan ekonomi kuantitatif. Skema-skema proyek hijau kerap didesain untuk memenuhi target emisi atau menaikkan rating investasi, tetapi melupakan dimensi keadilan sosial dan ekologis. Green project yang tidak memperhitungkan HAM, tidak melibatkan komunitas lokal, dan hanya berorientasi pasar akan berujung pada praktik green grabbing—yakni perampasan lahan atas nama lingkungan. Konservasi tanpa komunitas bukan solusi, tetapi bentuk baru dari eksklusi. Kebijakan fiskal seharusnya menjadi jembatan untuk mengoreksi ketimpangan historis ini. Anggaran negara mesti diarahkan untuk mendanai transisi ekologi yang adil, berbasis komunitas, dan berpihak pada rakyat kecil. Artinya, reformasi tata kelola anggaran tidak hanya soal teknis, tetapi soal keberpihakan: siapa yang dibela dan siapa yang ditinggalkan.
“Anggaran Hijau” Suatu Keniscayaan
Jika Indonesia ingin benar-benar bertransformasi menjadi negara berdaulat, adil, dan berkelanjutan pada 2045, maka strategi fiskalnya harus berubah. Bukan lagi semata mengejar indikator makro, melainkan mengukur seberapa besar anggaran negara membebaskan masyarakat dari kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian hutan, dan menghormati kearifan lokal.
Pada fase awal, penting untuk mengintegrasikan nilai jasa ekosistem dalam penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) – terutama di sektor kehutanan. Hal ini mengingat tarif PNBP relatif rendah dan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya kayu tanpa mempertimbangkan nilai ekologisnya seperti konservasi air, penyerapan karbon, dan keanekaragaman hayati. Pendekatan yang digunakan yakni Ecosystem Services Valuation (ESV). Pendekatan ini mencoba menunjukkan bahwa nilai ekonomi konservasi jauh lebih tinggi dibandingkan eksploitasi kayu, meski dengan dalih “deforestasi legal” melalui izin yang murah. Untuk itu, reformulasi tarif PNBP yang mencakup nilai ekologis, peningkatan tarif berbasis konservasi, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan pendekatan ekologis menjadi keniscayaan. Usulan skema ini ditawarkan dalam tulisan Gurnadi Ridwan dan Gulfino Guevarrato, para peneliti FITRA.
Pada tahap implementasi, sebagaimana dalam tulisan Triono Hadi, Dewan Nasional FITRA, penting untuk memastikan keberpihakan anggaran dalam mendukung transformasi Ekonomi Hijau di sektor Forestry and Other Land Use (FOLU), sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Meskipun Indonesia telah menetapkan target ambisius melalui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030, realisasinya masih terbentur oleh lemahnya alokasi anggaran dan inkonsistensi kebijakan. Sektor FOLU yang merupakan penyumbang emisi terbesar sekaligus memiliki potensi besar sebagai penyerap karbon, belum mendapatkan dukungan fiskal yang memadai, baik dari APBN maupun APBD. Ironisnya, penerimaan negara masih bertumpu pada aktivitas ekstraktif yang memperparah deforestasi.
Oleh karena itu, perlu segera dilakukan reformasi anggaran dengan memperkuat alokasi untuk konservasi, restorasi, dan pengelolaan hutan lestari, memperluas insentif fiskal seperti Ecological Fiscal Transfer (EFT), serta mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam pembiayaan berbasis hasil guna memastikan keberlanjutan jangka panjang dan pencapaian target iklim nasional. Agenda fiskal hijau tidak boleh hanya menjadi dokumen. Ia harus hadir di desa-desa yang merawat hutan, di komunitas adat yang menjaga air dan udara, dan di sawah-sawah yang melawan kekeringan.
Di tangan negara ada tanggung jawab besar untuk menjadikan anggaran sebagai alat keberpihakan, bukan sekadar pencapaian teknokratis. Kini, saatnya menjadikan fiskal hijau bukan sekadar komitmen di atas kertas, tetapi sebagai jantung pembangunan yang berpihak pada rakyat dan bumi Indonesia.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para penulis Bunga Rampai ini: Delima Silalahi, Eko Cahyono, Nizhar Marizi, Gurnadi Ridwan, Gulfino Guevarrato, Lisno Setiawan, M. Yasir Sani, Mohammad Faisal, Prof. Bustanul Arifin, dan Triono Hadi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada The Asia Foundation, Ibu Hana A. Satriyo (Country Representative The Asia Foundation), Mas Alam Surya Putra, Dwi Nugroho (Mas Hoho) dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) atas dukungan dan kerjasamanya sehingga buku Bunga Rampai ini rampung serta kawan-kawan Seknas FITRA, Betta Anugrah, Arrum Bakti, Eva Mulyanti, Bernard Allvitro dan Atmoko Didi.