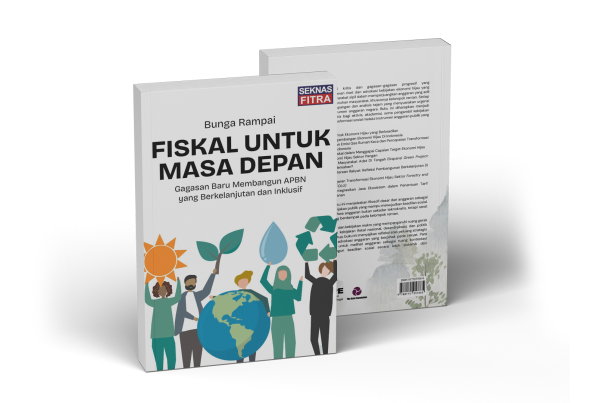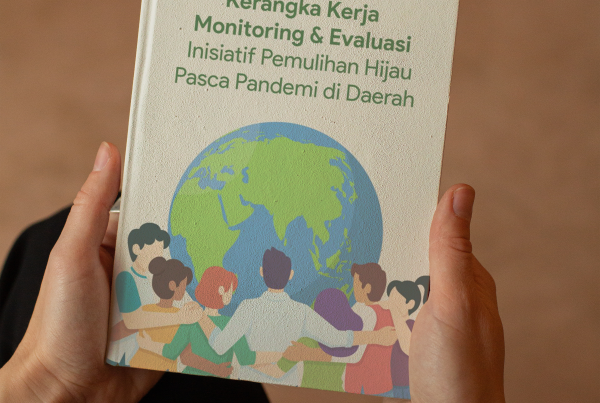Dalam konteks pemulihan ekonomi dalam penanganan pandemi COVID-19, kebijakan fiskal menjadi strategi Pemerintah Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan mengalokasikan berbagai stimulus serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup antara lain peningkatan anggaran kesehatan, relaksasi pajak, dan peningkatan banutuan sosial untuk mencegah penyebaran virus, mendorong aktivitas usaha, dan mendorong daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal berperan sebagai counter-cyclical bagi perekonomian, menahan laju perlambatan ekonomi serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran.
Namun demikian, pengeluaran fiskal untuk pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19, belum sepenuhnya mengintegrasikan masalah kebijakan iklim dan lingkungan secara memadai. Masih banyak ruang perbaikan, yaitu memprioritaskan pengeluaran fiskal yang mendukung pemulihan hijau dan berinvestasi dalam solusi rendah karbon jangka panjang. Maka, kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mendukung ‘pemulihan hijau’ atau Green Recovery agar dapat mendukung transisi yang adil dan terjangkau sehingga aksi iklim dapat berdampak nyata pada pertumbuhan yang berkelanjutan, stabilitas keuangan dan fiskal, peningkatkan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Kebijakan fiskal hijau penting untuk diimplementasikan tidak hanya di tingkat pusat, namun juga di tingkat daerah, mengingat karakteristik tiap wilayah yang beragam baik dari segi geografis, ekonomi, maupun sosial. Risiko bencana yang semakin tinggi intensitasnya dan beragam di tiap daerah menuntut peran aktif dari Pemda untuk dapat mengalokasikan pendanaan yang terkait dengan perubahan iklim dan mendukung ke transisi ke perekonomian hijau.
Dalam aspek penerimaan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan tersendiri atas pungutan pajak maupun retribusi yang dapat memberikan dampak pada perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kewenangan tersebut telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) baik itu kewenangan Pemerintah Provinsi maupun kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di wilayah bersangkutan. Dari sisi belanja, pemerintah daerah memiliki dua jenis belanja lingkungan yakni belanja untuk lingkungan hidup dan juga belanja untuk perubahan iklim.
Instrumen pendanaan potensial yang dapat mendukung transisi pemulihan ekonomi hijau yang bersumber dari APBD dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan/atau mekanisme transfer daerah. Beberapa instrumen pajak daerah mencakup: (i) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), (iv) Pajak Air Permukaan, (v) Pajak Air Tanah, (vi) Pajak Alat Berat, (vii) Opsen PKB, (viii) Opsen BBNKB, dan (ix) Opsen MBLB. Adapun potensi pendanaan dari retribusi antara lain: (i) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (ii) Retribusi Pengolahan Limbah Cair, (iii) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, serta (iv) Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan. Selanjutnya, pemerintah daerah juga dapat mengimplementasikan instrumen transfer fiskal berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer/EFT) atau yang dikenal dalam skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE).
Bentuk ini merupakan upaya pendanaan inovasi dari pemerintah daerah dan telah diadopsi di beberapa daerah sebagai bantuan keuangan khusus (Bankeu) dengan model pengalokasian belanja transfer dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah disetiap wilayah yaitu: dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dan dari kabupaten ke desa berdasarkan pertimbangan kinerja ekologi yang sudah dicapai.
Studi ini berfokus pada potensi pendanaan yang mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau di tingkat provinsi dengan membahas secara khusus potensi pendanaan dan yang ada di empat provinsi yaitu Riau, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Tengah. Pendekatan sektoral dan fiskal diperhitungkan untuk membangun penilaian yang komprehensif terhadap potensi pendapatan untuk transisi perekonomian hijau. Studi ini menggunakan kombinasi metode kualitatif (seperti tinjauan literatur, wawancara mendalam dengan beberapa key stakeholders, FGD) dan metode kuantitatif (analisis pemilihan sektor potensial di daerah dengan menggunakan metode MCDA dan analisis Input-Output).
Dari hasil studi didapatkan bahwa keempat provinsi (Jawa Barat, Riau, NTB, dan Sulawesi Tengah) telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak dari perubahan iklim di masing-masing wilayahnya. Komitmen terhadap lingkungan hidup tergambarkan dari adanya berbagai program lingkungan (misalnya: Riau Hijau, Jabar Juara, NTB Zero Waste) yang didukung oleh regulasi dan dokumen rencana kebijakan di daerah baik itu RPJMD, RKPD, RAD-GRK, maupun RAD-API. Tiga dari provinsi di dalam studi yakni Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi percontohan dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon. Demikian pula, dua dari keempat provinsi tersebut yakni Riau dan Jawa Barat juga menjadi provinsi percontohan dalam penandaan anggaran daerah untuk penanganan iklim (RCBT). Selain itu, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu lokasi prioritas pelaksanaan REDD+. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengurangi kerusakan hutan, memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas tutupan hutan untuk membantu menurunkan tingkat emisi rumah kaca dan memperlambpat perubahan iklim. Namun demikian, komitmen lingkungan di tingkat daerah belum terefleksikan sepenuhnya dari besaran alokasi belanja untuk program lingkungan dari APBD. Proporsi belanja fungsi lingkungan hidup untuk keseluruhan provinsi percontohan studi masih sangat kecil yakni kurang dari 2% terhadap total belanja. Proposi belanja lingkungan yang terbesar ada di Provinsi Riau sebesar 1,6% atau setara dengan Rp140 miliar di tahun 2022. Sementara pada Provinsi Jawa Barat, share belanja tersebut masih jauh lebih kecil yakni sebesar 0,13% di tahun 2022 atau setara dengan Rp40,1 miliar. Hal ini tidak sebanding jika mencermati Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat yang cukup besar, utamanya bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Disisi lain, proporsi belanja Provinsi NTB di tahun yang sama tercatat sebesar 0.55% dari total belanja atau senilai Rp33 miliar. Provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang memiliki belanja fungsi lingkungan hidup paling rendah, hanya tercatat sebesar Rp3,9 M atau setara dengan 0,08% dari keseluruhan belanja.
Dari hasil pemetaan potensi sektor yang dapat mendukung transisi ke perekonomian hijau dengan menggunakan berbagai kombinasi metode pendekatan, disusun berbagai kebijakan dan potensi pendanaannya berdasarkan karakteristik di masing-masing Provinsi. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim dan lingkungan yang sangat besar, tentunya mengandalkan peran APBD saja tidaklah cukup. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendanaan alternatif lainnya untuk mendukung agenda pemulihan hijau di daerah seperti melibatkan peran swasta, lembaga donor internasional, hibah, serta pinjaman dari pemerintah pusat. Berbagai skema pendanaan untuk lingkungan yang dapat dimanfaatkan mencakup Payment for Ecosystem Services (PES), Public-Private Partnership (PPP), Blended Financing melalui platform SDGs Indonesia One oleh PT. SMI, Blended Financing melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Pooling Fund Bencana (PFB), serta pinjaman daerah.
Terakhir, untuk mewujudkan agenda pemulihan hijau diperlukan penguatan peran dan kolaborasi aktif dari para pemangku kepentingan atau stakeholders. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari beberapa lapisan penting mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pihak swasta, serta masyarakat. Strategi penguatan kelembagaan juga perlu dilakukan dengan membentuk lembaga manajemen keuangan untuk lingkungan di tingkat daerah. Pembentukan lembaga ini ditujukan agar kegiatan dan usaha pemulihan hijau dapat dipetakan, didukung, serta dievaluasi secara menyeluruh. Sebagai hasilnya, akan lebih banyak kegiatan pemulihan hijau dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan yang dapat dijalankan di tingkat daerah.