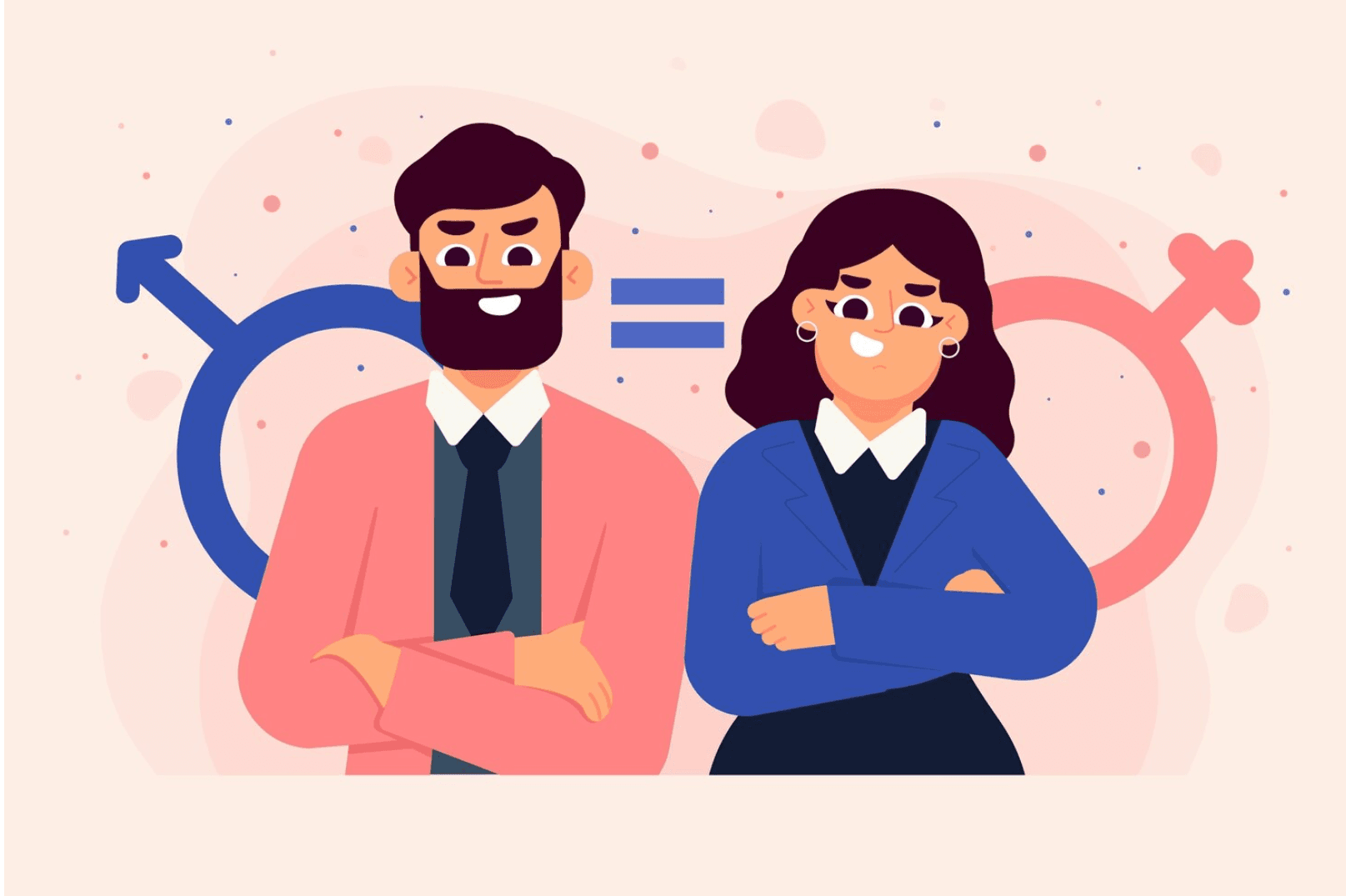Penulis: Misbah Hasan dan Rizqika Arrum Bakti
Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran pada 2026, agenda pembangunan berada pada fase yang menentukan karena menjadi kelanjutan langsung dari implementasi RPJMN 2025– 2029, pasca masa transisi di 2025. Pada tahap ini, isu kesetaraan gender semestinya tidak lagi diposisikan sebagai agenda tambahan, melainkan menjadi agenda utama secara strategis dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan kelompok rentan.
Pendekatan tersebut menegaskan pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui capaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melalui kemampuan negara dalam menjamin keadilan sosial serta membuka akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Komitmen pemerintah sejatinya telah tercermin secara tegas dalam Prioritas Nasional ke-4 (PN-4), yang secara eksplisit menempatkan isu kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas sebagai elemen fundamental dalam agenda pembangunan sumber daya manusia. Secara normatif, arah kebijakan ini menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap nilai inklusivitas dan keadilan sosial. Meski demikian, kuatnya pernyataan komitmen dalam dokumen kebijakan tidak selalu sejalan dengan hasil konkret di tingkat implementasi. Upaya mewujudkan pembangunan kesetaraan gender (PKG) pada praktiknya kerap berhadapan dengan kompleksitas kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang telah mengakar.
Potret Kesenjangan
Data BPS yang dipublikasikan pada April 2025 menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya unggul pada dua komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG), namun belum mampu dikonversi menjadi keunggulan sosial dan ekonomi. Perempuan unggul dalam aspek kesehatan, yakni Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 74,21 tahun, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 70,32 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan juga sedikit lebih tinggi, 13,39 tahun, sementara laki- laki hanya 12,99 tahun. Hal ini mencerminkan potensi generasi perempuan lebih besar di masa depan, meski belum sepenuhnya terwujud dalam capaian aktual.
Kesenjangan terjadi pada dimensi pendidikan riil. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan hanya 8,54 tahun, yaitu setara kelas dua sekolah menengah, tertinggal dari laki-laki yang mencapai 9,17 tahun (lulus SMP). Adapun kesenjangan paling tajam terlihat pada dimensi ekonomi. Pengeluaran per kapita laki-laki mencapai Rp17,35 juta per tahun, sementara perempuan hanya Rp9,92 juta per tahun. Angka ini tidak hanya mencerminkan perbedaan penghasilan yang dibelanjakan, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan akses perempuan terhadap pekerjaan layak, sumber daya ekonomi, dan posisi strategis dalam pasar kerja.
Ketimpangan akses yang dialami oleh perempuan dibuktikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih rendah. Ketika 84,66 persen laki-laki aktif dalam pasar kerja, TPAK perempuan hanya mencapai 56,42 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beban kerja domestik, keterbatasan akses lapangan kerja ramah perempuan, serta norma gender tradisional masih menjadi penghambat utama partisipasi ekonomi perempuan. Tidak heran apabila pengeluaran per kapita perempuan juga rendah.
Di luar indikator pembangunan formal, persoalan kekerasan berbasis gender menjadi cermin paling nyata dari ketimpangan relasi kuasa. Data menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya. Pada tahun 2024, dari 330.097 pengaduan kekerasan berbasis gender, hampir seribu kasus merupakan kekerasan berbasis gender online, menandai perluasan ruang kekerasan ke ranah digital. Perempuan juga mayoritas menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yakni 357 dari 640 korban.
Di ranah pengambilan keputusan, ketimpangan gender masih sangat mencolok. Komposisi anggota DPR RI didominasi laki-laki sebesar 77,54 persen, sementara perempuan hanya 22,46 persen, jauh dari prinsip keterwakilan setara minimal 30 persen. Di ranah birokrasi, proporsi perempuan yang menempati di posisi manajerial strategis tingkat nasional, baik eselon 1 maupun eselon 2 di kementerian/lembaga (K/L) baru mencapai 35,02 persen, menunjukkan adanya ‘dinding kaca’ yang sulit ditembus dan membatasi kemajuan perempuan ke posisi kepemimpinan strategis.
Secara keseluruhan, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran kemarin, belum banyak upaya yang dilakukan dalam mempercepat Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG). Data di atas bukan sekadar angka, melainkan potret nyata bahwa PKG terkesan ‘mandeg’ –stagnan. Kalaupun beranjak, perubahannya tidak signifikan. Sebagaimana dikemukakan Nancy Fraser dalam Fortunes of Feminism (2013), pengakuan kesetaraan tanpa redistribusi dan representasi hanya akan melahirkan keadilan semu.
Nancy Fraser mengenalkan pendekatan dua dimensi dalam mencapai keadilan gender, yaitu Dimensi Distribusi dan Pengakuan. Pada Dimensi Distribusi, Fraser menekankan ketidakadilan gender dalam struktur ekonomi masyarakat. Dimensi ini berkaitan dengan persoalan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan kesenjangan upah pada kerja manufaktur/profesional—yang didominasi oleh laki-laki— dengan kerja perawatan/domestik—yang didominasi oleh perempuan. Yang kedua, Fraser mengungkapkan dalam Dimensi Pengakuan, ketidakadilan gender berakar pada tatanan status masyarakat. Nilai budaya seperti norma dan stigma sosial, cenderung menihilkan pengalaman dan peran perempuan. Sehingga, muncul praktik diskriminatif yang kerap menempatkan perempuan ataupun kelompok rentan pada posisi yang tidak diuntungkan. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, negara harus berperan aktif mereduksi ketimpangan ekonomi berbasis gender, alih-alih bersikap netral. Selain itu, negara juga harus memberikan pengakuan terhadap pengalaman dan kebutuhan spesifik dari perempuan dan kelompok rentan.
Kekosongan Regulasi
Salah satu persoalan mendasar mengapa kesetaraan gender ‘mandeg’ adalah kekosongan regulasi. Sejak Gus Dur menerbitkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, hingga kini belum ada regulasi yang cukup kuat mendorong percepatan PUG. Inpres ini memang menegaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah (K/L/D) untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban. Namun, Inpres tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak cukup kuat menjadi landasan operasional implementasi PKG yang mengikat lintas sektor (K/L) dan lintas level pemerintahan (pusat- provinsi-kabupaten/kota). Akibatnya, implementasi PKG justru dianggap sebagai beban dan tambahan pekerjaan bagi K/L.
Di tingkat daerah, implementasi PUG diatur melalui Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Regulasi ini memang menyediakan kerangka awal kelembagaan dan operasionalisasi PUG, namun substansinya belum sepenuhnya selaras dengan dinamika tata kelola pemerintahan daerah, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta tuntutan akuntabilitas pembangunan saat ini. Permendagri ini juga sulit mendorong kepatuhan lintas perangkat daerah dan belum mampu menempatkan PUG sebagai kewajiban strategis seluruh aktor pembangunan di daerah, bukan semata urusan perangkat daerah pengampu pemberdayaan perempuan.
Minimnya Anggaran Gender
Persoalan berikutnya adalah kurang seriusnya pemerintah dan pemerintah daerah (K/L/D) menyusun Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG adalah instrumen untuk memastikan program/kegiatan benar- benar menjawab kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan, laki-laki, dan kelompok marginal. Namun pada praktiknya, ARG sering dipersepsikan sebagai tambahan beban administratif, bukan bagian integral dari anggaran berbasis kinerja dan memastikan kualitas belanja responsif gender dan inklusif, sehingga tidak dikerjakan secara benar dan konsisten.
Memang, dalam menyusun ARG harus melalui analisis gender ‘Gender Analysis Pathway (GAP)’ dilengkapi pernyataan anggaran gender atau Gender Budget Statement (GBS). Ini yang membutuhkan kemampuan khusus. Untuk itu, saat ini tengah dikembangkan Gender Action Budget, yakni analisis gender yang dintegrasikan langsung ke dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) K/L/D sebagai upaya mempermudah menyusun ARG.
Padahal dari sisi besaran anggaran, kegiatan dan anggaran K/L yang dikategorikan responsif gender masih relatif kecil. ARG di tingkat nasional (K/L) sebesar Rp63,61 triliun pada 2022 dan naik menjadi Rp70,02 triliun pada 2023. Namun di dua tahun terakhir, terjadi penurunan ARG yang sangat signifikan. Alokasi ARG menjadi Rp43,25 triliun pada 2024 dan hanya Rp26,7 triliun pada 2025, turun sangat signifikan. Rata-rata ARG tersebut hanya dua persen dari total Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp2.486,7 triliun (2024) dan Rp2.701,4 triliun (2025). Minimnya ARG memperkuat sinyal bahwa pemerintah tidak benar-benar serius menangani kesenjangan gender di Indonesia.
Agenda Ke Depan
Melihat realitas kesenjangan dan ketimpangan gender serta berbagai tantangan di atas, pemerintah yang dipimpin Prabowo-Gibran perlu mengambil langkah strategis sebagai berikut:
Pertama, menutup kekosongan regulasi melalui payung hukum yang mengikat. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tentang Percepatan Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG). Regulasi ini diharapkan melampaui pendekatan administratif Inpres 9/2000 dengan menetapkan indikator PKG yang terukur, berbasis kinerja, dan wajib dipenuhi oleh seluruh tingkatan pemerintahan. Dengan kata lain, menyediakan mekanisme kepatuhan, sanksi administratif, dan reward berupa insentif fiskal.
Kedua, menjadikan ARG sebagai instrumen untuk mengukur kualitas belanja negara. ARG tidak boleh diposisikan sekadar disusun dan ditandai (tagging), melainkan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas belanja melalui proses tracking dan optimizer belanja K/L. Pemerintah perlu mewajibkan Gender Analysis Pathway (GAP) sebagai bagian dari business process perencanaan, mengaitkan kualitas GAP dan ARG dengan penilaian kinerja K/L, serta memperkuat peran inspektorat dalam quality assurance ARG.
Ketiga, memfokuskan intervensi pada sektor dengan kesenjangan gender terparah. Berdasarkan data IPG, IKG, dan kesenjangan lainnya, kebijakan nasional harus memprioritaskan peningkatan partisipasi dan kualitas kerja perempuan, penguatan kepemimpinan dan keterwakilan politik perempuan, serta pencegahan kekerasan berbasis gender (termasuk kekerasan digital dan praktik berbahaya).
Tanpa fokus pada sektor strategis, program/kegiatan kesetaraan gender akan terjebak pada proses administratif dan simbolik dengan anggaran kecil, sehingga tidak mempunyai daya ungkit dan tidak berdampak apapun pada percepatan Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG).
Rizqika Arrum Bakti adalah peneliti Seknas FITRA, lulusan Program Studi Kajian Gender di Universitas Indonesia yang menekuni bidang Pelayanan Dasar dan Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Misbah Hasan adalah alumni Magister Kajian Gender Universitas Indonesia dan Sekretaris Jenderal FITRA periode 2018-sekarang.
Sumber: https://tirto.id/menagih-janji-pembangunan-kesetaraan-gender-prabowo-gibran-hpD3?t=1768991993033